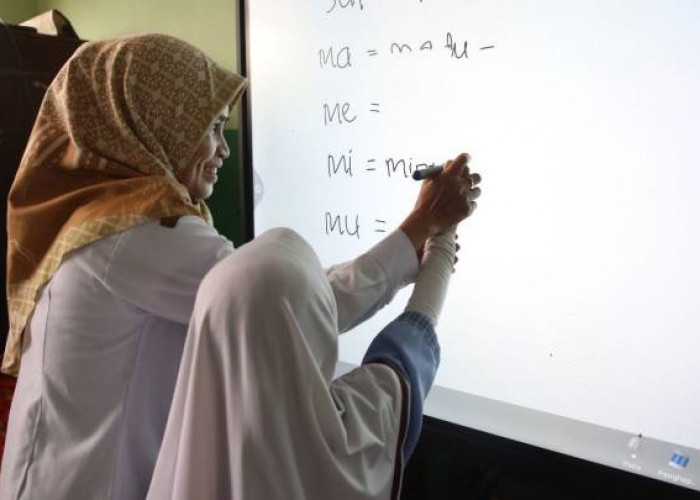Konsistensi Ebiet G. Ade Melagukan Puisi yang Berbuah Satyalencana Kebudayaan

Ebiet G. Ade teguh menembangkan puisi tentang alam, keluarga, dan romansa selama hampir empat dekade. Sampai tak ingat lagi sudah berapa orang yang bilang hidup mereka berubah karena lagu-lagunya. COBALAH ”eksperimen” kecil ini. Berbaring di tempat tidur, pasang earphone, matikan lampu, lalu putarlah Berita kepada Kawan. Kawan coba dengar apa jawabnya//Ketika dia kutanya mengapa//Bapak ibunya tlah lama mati//Ditelan bencana tanah ini. Ketika pada bagian itu kemudian mendadak terbayang tsunami Aceh atau gempa Lombok, lalu tiba-tiba ada yang meleleh di sudut mata, jangan malu. Anda tak sendirian. Karya legendaris Ebiet G. Ade itu memang tak pernah gagal menggugah rasa haru. Misalnya, yang juga tampak saat Ebiet mendendangkannya di Anugerah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni Tradisi 2018 Rabu malam lalu (26/9). “Tentu (awalnya, Red) tidak berpikir jadi background peristiwa bencana. Rasa lagu itu sebenarnya normatif saja bahwa bencana harus kita sikapi dengan arif,” tuturnya saat ditemui Jawa Pos seusai acara. Dalam acara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, itu, Ebiet dianugerahi Satyalencana Kebudayaan dari presiden Indonesia. Yang diserahkan melalui Mendikbud Muhadjir Effendy. Kriteria penerima penghargaan itu adalah mereka yang telah mengabdi di bidang kebudayaan sejak minimal berusia 30 tahun. Ebiet telah jauh melampaui parameter tersebut. Rekaman pertamanya dilakukan di Jackson Record pada 1979. Saat usia pria yang terlahir di Banjarnegara, Jawa Tengah, dengan nama Abid Ghoffar bin Aboe Dja’far itu baru berusia 25 tahun. Sejak itu dia konsisten berkarya. Sudah 22 album studio yang telah dia lahirkan. Album kompilasi malah lebih banyak lagi: lebih dari 30. “Negara memberi penghargaan itu. Saya harus merasa bahagia atas penghargaan ini,” ungkap pelantun Camelia yang melegenda tersebut. Hampir semua lagu yang dia nyanyikan karya sendiri. Kecuali, mengutip Wikipedia, Surat dari Desa yang ditulis Oding Arnaldi dan Mengarungi Keberkahan Tuhan yang ditulis bersama dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Konsistensi dia juga terlihat dalam penulisan lirik. Lagu-lagu Ebiet, bisa dibilang, adalah puisi-puisi yang dinyanyikan. Musikalisasi puisi kalau dalam bahasa sekarang. Suami Yayuk Sugianto itu memang berlatar belakang penyair. Besar dalam asuhan penyair legendaris Umbu Landu Paranggi di kawasan Malioboro, Jogjakarta. Bersama, antara lain, Emha Ainun Nadjib, Eko Tunas, dan E.H. Kartanegara. Lirik-liriknya banyak bercerita tentang alam, keluarga, dan romansa. Lebih khusus lagi tentang alam: kontemplasi atas bencana yang terjadi. Simak, misalnya, penggalan Untuk Kita Renungkan: Anak menjerit-jerit//asap panas membakar//Lahar dan badai menyapu bersih//Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat//Bahwa kita mesti banyak berbenah. “Kemampuan saya ya hanya seperti ini, memotret keadaan sekeliling saya dan menerjemahkannya dalam musik yang sederhana dan mudah dicerna,” ungkapnya. Tapi, di waktu lain, Ebiet juga bisa bernyanyi dengan indahnya. Tentang kekasih, tentang cinta. Seperti dalam Camelia 2: Inginku berlari//Mengejar seribu bayangmu Camelia//Tak peduli kau kuterjang//Biar pun harusku tembus padang ilalang. Menurut Ebiet, kehidupan bermusiknya banyak dipengaruhi cerita masa kecil. Tak pernah tebersit di benaknya jika lirik-lirik yang dituliskannya itu kelak akan membuat namanya besar. Maklum saja, sewaktu kecil dia tidak pernah bermimpi menjadi musisi. Cita-citanya kala kecil adalah insinyur, pelukis, dan dokter. “Saya beruntung karena beberapa kali karya saya menjadi inspirasi bagi beberapa orang,” tutur ayah empat anak itu. Berkali-kali Ebiet mengetahui hal itu dari fansnya. Dia sampai tidak ingat sudah berapa orang yang pernah bilang hidup mereka berubah setelah mendengar lagu-lagu Ebiet. “Saya anggap saja itu sebagai ladang ibadah,” imbuhnya. Pria yang berulang tahun setiap 21 April itu mengaku, dirinya sempat khawatir penghargaan seprestisius Satyalencana Kebudayaan hanya diberikan kepada seniman yang bermain di wilayah populer. Teguh berkarya di wilayah yang bisa dibilang lebih condong ke folk, yang tentu saja terasa asing di tengah ingar bingar digitalisasi musik sekarang ini, Ebiet memang bisa dibilang “melawan arus” industri musik. Karena itu, dia bahagia sekaligus bangga ketika Agustus lalu diberi tahu mendapatkan Satyalencana Kebudayaan. “Penghargaan tersebut wujud perhatian negara kepada seniman,” katanya. Apresiasi dari pemerintah itu membuat semangat bermusiknya yang memang tak pernah padam semakin menyala. Meski memang album studio terakhirnya sudah dirilis pada 2013. Hari-harinya kini banyak dihabiskan untuk traveling bersama keluarga. Tapi, ayah pemusik Aderaprabu Lantip Trengginas atau dikenal dengan Adera itu masih terlibat dalam permusikan tanah air. Dengan menjadi komisioner di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. “Tugasnya mengurus royalti musik yang perputarannya ada di Indonesia,” tuturnya. Tapi, gitar tentu tetap jadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Begitu pula dengan menulis puisi atau lirik. Melagukannya adalah bagian dari cara menampilkannya. Karena sedari muda Ebiet sadar dirinya tipe penyair yang tak pandai membacakan karya. “Musik Indonesia itu sekarang sudah sangat baik. Tinggal kita sebagai bangsa saling menghargai dan menjaga,” ungkapnya. Dan, di usianya yang sudah 64 tahun kini, dia akan menikmati semua itu tidak lagi dari dekat. Dia memilih menjadi ”kupu-kupu kertas, yang terbang kian kemari”. (jpg/bha)
Sumber: