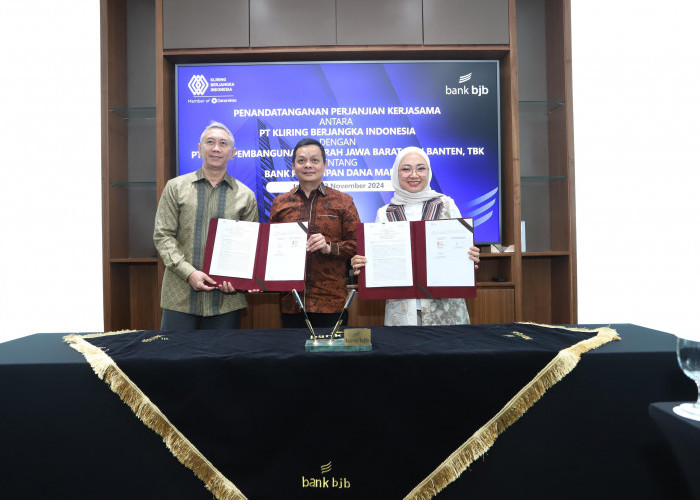Ekonomi RI Sudah Lampu Kuning

Jakarta - Layaknya pertandingan tinju, perekonomian RI tengah mendapatkan pukulan bertubi-tubi. Setelah didera perlambatan konsumsi masyarakat, ekonomi RI dihantam liarnya pergerakan dolar AS, ditambah lagi defisit neraca perdagangan RI semakin melebar. Jika ditanya bagaimana kondisi ekonomi RI saat ini, Ekonom sekaligus Direktur Center of Reform on Economics (Core) Muhammad Faisal mengatakan sudah lampu kuning. Masih jauh memang jika disamakan dengan kondisi ekonomi RI saat krisis moneter (krismon) pada 1998. "Kalau bicara secara makro sebetulnya kalau dikatakan sebagai krisis ini belum. (Tapi) sudah lampu kuning," tutur Faisal seperti dikutip detik.com, Rabu (23/5). Gejolak ekonomi RI mulai terasa di tahun lalu, masyarakat terasa mengerem konsumsinya. Pemerintah boleh saja saat itu menampik bahwa daya beli masyarakat baik-baik saja, tapi buktinya banyak perusahaan ritel yang mengurangi jumlah gerainya bahkan ada yang guling tikar. Buktinya kembali diperkuat ketika Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa tingkat konsumsi rumah tangga Indonesia pada 2017 di level 4,95%. Angka itu melambat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang tumbuh 5,01%. "Apakah itu lantas kemudian dikatakan kontraksi? Tidak sebenarnya, karena masih tumbuh tidak minus," tuturnya. Namun sayangnya kontribusi konsumsi rumah tangga RI sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, sekitar lebih dari 50%. Sehingga ketika konsumsi rumah tangga melambat dampaknya sangat terasa terhadap kelancaran aktivitas ekonomi hingga ke hulu. Belum selesai permasalahan masyarakat yang lebih irit, ekonomi RI kembali dihantam dari sisi nilai tukar. Dolar AS tiba-tiba mengamuk. Bayangkan saja dari awal tahun dolar masih tenang di sekitar Rp 13.500, tiba-tiba menguat hingga posisi Rp 14.200. Penyebabnya sistemik, sumbunya dari negeri adidaya Paman Sam. Bank Sentral AS The Fed akan menaikan suku bunga. Alhasil banyak dana asing yang keluar dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Faisal mengatakan, dampak dari pelemahan rupiah yang akan terasa cukup besar. Pertama bisa kembali menghantam konsumsi rumah tangga, sebab akan banyak produk-produk impor ataupun berbasis bahan baku impor yang akan naik harganya. "Konsumsi dalam negeri kita banyak bergantung dari luar. Kita banyak impor pangan hingga minyak. Jadi dampaknya juga ke harga BBM dan tarif listrik. Ini yang menyebabkan mempengaruhi daya beli rumah tangga," terangnya. Sementara pengaruhnya ke industri akan menurunkan daya saing. Sebab banyak dari industri dalam negeri meski yang berorientasi ekspor bahan bakunya masih bergantung impor. Sehingga biaya produksi akan meningkat. Imbasnya daya saing industri nasional di tingkat nasional maupun internasional menurun. Hantaman yang ketika adalah melebarnya defisit neraca perdagangan. BPS juga mencatat neraca perdagangan RI pada April 2018 mengalami defisit US$ 1,63 miliar. Ekspor tercatat US$ 14,47 miliar, sementara impornya US$ 16,09 miliar. Bank Indonesia (BI) bahkan memprediksi tahun ini defisit transaksi berjalan diperkirakan berada di US$ 23 miliar atau melebar menjadi 2,3% dari produk domestik bruto (PDB). Permasalahan defisit perdagangan memang juga terimbas dari pelemahan nilai tukar dan kenaikan harga minyak. Sebab di sisi migas, Indonesia masih sangat besar melakukan impor. Jadi ketika harga minya naik, impor Indonesia membengkak. Sementara dari sisi ekspor, sayangnya Indonesia masih bergantung pada barang-barang komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit. Sayangnya kedua komoditas itu bergantung pada harga pasar bukan fluktuasi nilai tukar. Apalagi saat ini negara-negara tujuan ekspor komoditas Indonesia seperti Eropa dan India tengah mengurangi penggunaan batu bara dan kelapa sawit dengan alasan lingkungan. Meski begitu Faisal menegaskan bahwa ekonomi RI belum krisis. Sebab berkaca dari pengalaman 1998, saat krisis pertumbuhan ekonomi RI minus selama 3 kuartal. Sementara saat ini ekonomi Indonesia masih tumbuh di kisaran 5%.(dtc)
Sumber: